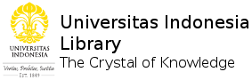Full Description
| Cataloguing Source | LibUI ind rda |
| Content Type | text (rdacontent) |
| Media Type | unmediated (rdamedia); computer (rdamedia) |
| Carrier Type | volume (rdacarrier); online resource (rdacarrier) |
| Physical Description | xiv, 119 pages : illustration ; 28 cm + appendix |
| Concise Text | |
| Holding Institution | Universitas Indonesia |
| Location | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
- Availability
- Digital Files: 1
- Review
- Cover
- Abstract
| Call Number | Barcode Number | Availability |
|---|---|---|
| S2572 | 14-18-785902150 | TERSEDIA |
| No review available for this collection: 20286747 |
Abstract
ABSTRAK
Masa lanjut usia (selanjutnya disebut lansia) adalah tahap akhir perkembangan kehidupan seseorang dan merupakan masa yang paling dekat dengan kematian. Pada masa ini terjadi proses menua {aging) yang ditandai dengan terjadinya penurunan kemampuan fisik yang tidak bisa dihindari dan antara lain bisa meningkatkan terjadinya. kecelakaan dan timbulnya penyakit. Semakin bertambah tua seseorang dengan segala kemunduran yang dialaminya, pikiran-pikiran mengenai kematian mulai timbul. Teori Levinson (1978) yang menekankan pada adanya masa transisFpada setiap taliap kehidupan manusia pun menganggap bahwa pada saat itu kehidupan tidak lagi dipandang sebagai waktu yang kita miliki sejak kita dilahirkan, tapi lebih sebagai waktu yang tersisa sampai pada akliir kehidupan. Erikson (1963) menambahkan pentingnya merencanakan kehidupan dalam sisa waktu tersebui mengisinya dengan hal-hal yang berguna dan pada akhirnya mampu menghadapi kematian tanpa rasa takut yang berlebihan. Jika mereka percaya akan adanya kehidupan setelah kematian, maka penting adanya persiapan-persiapan untuk memasuki suatu babak kehidupan baru. Dalam kehidupan sehari-hari, profesi yang paling sering menghadapi kematian adalah dokter. Sebagai ahli dalam bidang kesehatan, sebagian besar waktu dan hidupnya dihabiskan untuk mengobati orang sakit, bahkan untuk dokter spesialis tertentu seringkali harus berhadapan dengan pasien-pasien yang menderita terminal diseases. Menurut Kasper (dalam Feifel, 1959) seorang dokter mempunyai pekerjaan tambahan untuk melawan takdir manusia : kematian. Dalam ha! ini kematian dilihat sebagai kenyataan obyektif yang terjadi pada orang lain; padahal kematian terjadi pada semua orang, tak terkecuali dirinya. Kematian sebagai kenyataan obyektif tentu berbeda dengan dekatnya kematian sebagai penghayatan subyektif. Di balik semua usalianya untuk mengobati pasien dan menghindarkan mereka dari kematian, dokter tahu bahwa dia akan menghadapi kematian juga seperti pasien-pasiennya selama ini (Wheelis, 1958; dalam Feifel, 1959), Maka bagaimana para dokter menghayati keadaan dirinya sebagai manusia yang tidak terlepas dari kematian -apalagi saat mereka memasuki masa lansia- serta bagaimana persiapan-persiapan yang mereka lakukan, merupakan permasalahan yang menarik. Penghayatan terhadap keadaan yang dialami seseorang sehubungan dengan kematian merupakan masalah yang sensitif dan seringkali bersifat subyektif, baik itu menyangkut sikap, emosi maupun proses-proses internal lainnya (Bern; dalam Deaux & Wrightsman, 1984); maka penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan mengambil 6 orang pensiunan dokter yang berusia antara 60-79 tahun sebagai subyek, yaitu meliputi 2 kategori penggolongan menurut Burnside (1979; dalam Craig, 1986) yaitu The Young-Old (60-69 tahun) dan The Middle-Aged Old (70-79 tahun). Penelitian ini mengambil pensiunan dokter sebagai subyek karena kehilangan pekerjaan yang disebabkan karena faktor usia menyadarkan seseorang bahwa dirinya sudah memasuki tahap akliir dalam kehidupan. Dengan berkurangnya aktivitas dan tuntutan masyarakat, lansia pun mulal menyadari kondisi fisiknya yang menurun serta merasakan keluhan-keluhan kesehatan; saat inilah lansia mulai berpikir akan akhir kehidupannya. Profesi dokter yang dibutulikan dalam penelitian ini adalah spesialisasi yang memungkinkan dokter tersebut dalam masa kerjanya berhadapan dengan banyak kematian pasien, sehingga wawasan pengetahuan dan pengalaman yang 'lebih' akan membantu mengungkapkan penghayatannya akan kematian.Usia subyek tidak melebihi 80 tahun, karena menurut Burnside umumnya orang yang telah memasuki usia 80 tahun keatas akan mengalami penurunan kondisi kesehatan, penurunan kemanipuan adaptasi, serta peningkatan kesulitan dalam berhubungan dengan sekelilingnya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dan dalam peiaksanaannya pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam {depth interview) karena menyangkut perasaan dan pengalaman, serta penghayatan subyek tentang hal yang sangat sensitif. Wawancara ini dibantu dengan pedoman wawancara berupa kuesioner yang bersifat open-ended. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa subyek penelitian menyadari adanya penurunan kondisi fisik dan mental sebagai akibat dari proses menua. Menghadapi hal itu subyek memilih untuk tetap beraktivitas, tetap praktek walaupun dalam frekwensi yang terbatas, bersibuk diri dengan hobi yang sebeiumnya tidak sempat dilakukan, atau memilih untuk lebih banyak berkumpul dengan keluarga. Mengenai kegiatan praktek, hal ini tampaknya berkaitan dengan usaha mereka untuk menghayati eksistensi mereka sebagai keberadaan yang bermakna. Dengan melanjutkan prakteknya mereka merasa tetap bisa berguna sekaligus terhindar dari kesadaran akan kemunduran flsik dan mental serta rasa ketidakberdayaan yang sering dialami iansia, Penyakit yang didcrita pun tidak menghalangi mereka untuk tetapoptimis, dilihat dari usaha mereka untuk melawan penyakit itu. Mengenai kematian yang selama masa kerjanya dilihat sebagai sesuatu yang terjadi diluar diri, subyek menyadari bahwa hal itu pun akan terjadi pada diri mereka. Subyek mempunyai pandangan religius mengenai kematian; mereka berpendapat bahwa kematian merupakan takdir yang berlaku bagi manusia, dan cepat atau lambat pasti akan tiba saatnya tanpa mungkin menghindarinya. Bagi subyek, kematian adalah saal peralihan menuju kehidupan lain yang lebih kekal. Karena pandangan ini diperoleh dan ajaran agama masing-masing, maka subyek pada sisa hidupnya umumnya berusaha untuk meiaksanakan perintah agamanya masing-masing, berbuat baik kepada sesama agar mendapat pahala dalam kehidupan sesudah kematian. Bahkan ada diantaranya subyek yang lebih optimistik menghadapi kematian, karena percaya bahwa kehidupan sesudah kematian lebih banyak menjanjikan kenikmatan. Subyek juga menyatakan harapan agar kematiannya tidak didahului oleh rasa sakit dan beban penderitaan baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Sebagai realisasi dari kesadaran akan datangnya kematian, subyek mulai melakukan persiapan-persiapan. Persiapan itu meliputi hal-hal yang bersifat material seperti menyediakan rumah yang layak bagi keluarganya, tabungan dan deposito untuk menghindari kesulitan ekonomi keluarga, dan mempersiapkan pembagian warisan agar sepeninggalnya nanti tidak terjadi sengketa antara sesama anggota keluarga. Persiapan material ini lebih ditujukan pada keluarga yang ditinggalkan seperti anak, istri, dan cucu. Dalam hal ini tampaknya kedua subyek wanita dalam penelitian tidak terlalu terbebani. Mungkin karena kedua subyek ada dalam situasi sedemikian rupa sehingga beban pikiran mengenai persiapan material tidak seberat pada subyek pria; satu subyek sudah bercerai dan subyek lain tidak menikah. Selain itu subyek penelitian tidak menyinggung urusan pemakaman sebagai salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan. Hasil lain yang menarik adalah kepasrahan salah satu subyek yang luar biasa sehingga tidak membuat persiapan apapun yang bersifat material. Untuk ketenangan diri subyek dalam menghadapi kematian sebagai sesuatu yang tidak diketahui secara pasti, subyek meningkatkan sikap religius; antara lain dengan menjalankan kehidupan yang sesuai dengan ajaran agama masing-masing, banyak mawas diri, meiaksanakan shalat lima waktu, menunaikan ibadah haji, rajin pergi ke gereja, rajin mengikuti pengajian dan ceramah keagamaan, membaca bukubuku keagamaan, dan kegiatan lainnya yang dapat mempertebal keyakinan agama masing-masing. Subyek umumnya sudah merasa cukup puas dengan kehidupannya selama ini dan tidak merasa perlu meminta apa-apa lagi kecuali hanya bersyukur kepada Tuhan atas segala karunianya. Selain keyakinan agama yang kuat, hal yang juga mendukung ketenangan subyek ialah keberadaan mereka dalam lingkungan keluarga yang akrab satu sama lain. Diharapkan hasil penelitian ini -walaupun hasilnya belum dapat digeneralisasikan- dapat memberikan sumbangan pengetahuan dalam hal kematian yang masih sangat langka di Indonesia; kliususnya dari tinjauan ilmu psikologi, terutama bagaimana lansia mengatasi rasa takutnya terhadap kematian dan memberikan gambaran mengenai apa saja yang perlu dipersiapkan untuk dapat menghadapi kematian dengan tenang, sehingga mereka dapat mempergunakan sisa hidupnya dengan hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya.
Masa lanjut usia (selanjutnya disebut lansia) adalah tahap akhir perkembangan kehidupan seseorang dan merupakan masa yang paling dekat dengan kematian. Pada masa ini terjadi proses menua {aging) yang ditandai dengan terjadinya penurunan kemampuan fisik yang tidak bisa dihindari dan antara lain bisa meningkatkan terjadinya. kecelakaan dan timbulnya penyakit. Semakin bertambah tua seseorang dengan segala kemunduran yang dialaminya, pikiran-pikiran mengenai kematian mulai timbul. Teori Levinson (1978) yang menekankan pada adanya masa transisFpada setiap taliap kehidupan manusia pun menganggap bahwa pada saat itu kehidupan tidak lagi dipandang sebagai waktu yang kita miliki sejak kita dilahirkan, tapi lebih sebagai waktu yang tersisa sampai pada akliir kehidupan. Erikson (1963) menambahkan pentingnya merencanakan kehidupan dalam sisa waktu tersebui mengisinya dengan hal-hal yang berguna dan pada akhirnya mampu menghadapi kematian tanpa rasa takut yang berlebihan. Jika mereka percaya akan adanya kehidupan setelah kematian, maka penting adanya persiapan-persiapan untuk memasuki suatu babak kehidupan baru. Dalam kehidupan sehari-hari, profesi yang paling sering menghadapi kematian adalah dokter. Sebagai ahli dalam bidang kesehatan, sebagian besar waktu dan hidupnya dihabiskan untuk mengobati orang sakit, bahkan untuk dokter spesialis tertentu seringkali harus berhadapan dengan pasien-pasien yang menderita terminal diseases. Menurut Kasper (dalam Feifel, 1959) seorang dokter mempunyai pekerjaan tambahan untuk melawan takdir manusia : kematian. Dalam ha! ini kematian dilihat sebagai kenyataan obyektif yang terjadi pada orang lain; padahal kematian terjadi pada semua orang, tak terkecuali dirinya. Kematian sebagai kenyataan obyektif tentu berbeda dengan dekatnya kematian sebagai penghayatan subyektif. Di balik semua usalianya untuk mengobati pasien dan menghindarkan mereka dari kematian, dokter tahu bahwa dia akan menghadapi kematian juga seperti pasien-pasiennya selama ini (Wheelis, 1958; dalam Feifel, 1959), Maka bagaimana para dokter menghayati keadaan dirinya sebagai manusia yang tidak terlepas dari kematian -apalagi saat mereka memasuki masa lansia- serta bagaimana persiapan-persiapan yang mereka lakukan, merupakan permasalahan yang menarik. Penghayatan terhadap keadaan yang dialami seseorang sehubungan dengan kematian merupakan masalah yang sensitif dan seringkali bersifat subyektif, baik itu menyangkut sikap, emosi maupun proses-proses internal lainnya (Bern; dalam Deaux & Wrightsman, 1984); maka penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan mengambil 6 orang pensiunan dokter yang berusia antara 60-79 tahun sebagai subyek, yaitu meliputi 2 kategori penggolongan menurut Burnside (1979; dalam Craig, 1986) yaitu The Young-Old (60-69 tahun) dan The Middle-Aged Old (70-79 tahun). Penelitian ini mengambil pensiunan dokter sebagai subyek karena kehilangan pekerjaan yang disebabkan karena faktor usia menyadarkan seseorang bahwa dirinya sudah memasuki tahap akliir dalam kehidupan. Dengan berkurangnya aktivitas dan tuntutan masyarakat, lansia pun mulal menyadari kondisi fisiknya yang menurun serta merasakan keluhan-keluhan kesehatan; saat inilah lansia mulai berpikir akan akhir kehidupannya. Profesi dokter yang dibutulikan dalam penelitian ini adalah spesialisasi yang memungkinkan dokter tersebut dalam masa kerjanya berhadapan dengan banyak kematian pasien, sehingga wawasan pengetahuan dan pengalaman yang 'lebih' akan membantu mengungkapkan penghayatannya akan kematian.Usia subyek tidak melebihi 80 tahun, karena menurut Burnside umumnya orang yang telah memasuki usia 80 tahun keatas akan mengalami penurunan kondisi kesehatan, penurunan kemanipuan adaptasi, serta peningkatan kesulitan dalam berhubungan dengan sekelilingnya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dan dalam peiaksanaannya pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam {depth interview) karena menyangkut perasaan dan pengalaman, serta penghayatan subyek tentang hal yang sangat sensitif. Wawancara ini dibantu dengan pedoman wawancara berupa kuesioner yang bersifat open-ended. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa subyek penelitian menyadari adanya penurunan kondisi fisik dan mental sebagai akibat dari proses menua. Menghadapi hal itu subyek memilih untuk tetap beraktivitas, tetap praktek walaupun dalam frekwensi yang terbatas, bersibuk diri dengan hobi yang sebeiumnya tidak sempat dilakukan, atau memilih untuk lebih banyak berkumpul dengan keluarga. Mengenai kegiatan praktek, hal ini tampaknya berkaitan dengan usaha mereka untuk menghayati eksistensi mereka sebagai keberadaan yang bermakna. Dengan melanjutkan prakteknya mereka merasa tetap bisa berguna sekaligus terhindar dari kesadaran akan kemunduran flsik dan mental serta rasa ketidakberdayaan yang sering dialami iansia, Penyakit yang didcrita pun tidak menghalangi mereka untuk tetapoptimis, dilihat dari usaha mereka untuk melawan penyakit itu. Mengenai kematian yang selama masa kerjanya dilihat sebagai sesuatu yang terjadi diluar diri, subyek menyadari bahwa hal itu pun akan terjadi pada diri mereka. Subyek mempunyai pandangan religius mengenai kematian; mereka berpendapat bahwa kematian merupakan takdir yang berlaku bagi manusia, dan cepat atau lambat pasti akan tiba saatnya tanpa mungkin menghindarinya. Bagi subyek, kematian adalah saal peralihan menuju kehidupan lain yang lebih kekal. Karena pandangan ini diperoleh dan ajaran agama masing-masing, maka subyek pada sisa hidupnya umumnya berusaha untuk meiaksanakan perintah agamanya masing-masing, berbuat baik kepada sesama agar mendapat pahala dalam kehidupan sesudah kematian. Bahkan ada diantaranya subyek yang lebih optimistik menghadapi kematian, karena percaya bahwa kehidupan sesudah kematian lebih banyak menjanjikan kenikmatan. Subyek juga menyatakan harapan agar kematiannya tidak didahului oleh rasa sakit dan beban penderitaan baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Sebagai realisasi dari kesadaran akan datangnya kematian, subyek mulai melakukan persiapan-persiapan. Persiapan itu meliputi hal-hal yang bersifat material seperti menyediakan rumah yang layak bagi keluarganya, tabungan dan deposito untuk menghindari kesulitan ekonomi keluarga, dan mempersiapkan pembagian warisan agar sepeninggalnya nanti tidak terjadi sengketa antara sesama anggota keluarga. Persiapan material ini lebih ditujukan pada keluarga yang ditinggalkan seperti anak, istri, dan cucu. Dalam hal ini tampaknya kedua subyek wanita dalam penelitian tidak terlalu terbebani. Mungkin karena kedua subyek ada dalam situasi sedemikian rupa sehingga beban pikiran mengenai persiapan material tidak seberat pada subyek pria; satu subyek sudah bercerai dan subyek lain tidak menikah. Selain itu subyek penelitian tidak menyinggung urusan pemakaman sebagai salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan. Hasil lain yang menarik adalah kepasrahan salah satu subyek yang luar biasa sehingga tidak membuat persiapan apapun yang bersifat material. Untuk ketenangan diri subyek dalam menghadapi kematian sebagai sesuatu yang tidak diketahui secara pasti, subyek meningkatkan sikap religius; antara lain dengan menjalankan kehidupan yang sesuai dengan ajaran agama masing-masing, banyak mawas diri, meiaksanakan shalat lima waktu, menunaikan ibadah haji, rajin pergi ke gereja, rajin mengikuti pengajian dan ceramah keagamaan, membaca bukubuku keagamaan, dan kegiatan lainnya yang dapat mempertebal keyakinan agama masing-masing. Subyek umumnya sudah merasa cukup puas dengan kehidupannya selama ini dan tidak merasa perlu meminta apa-apa lagi kecuali hanya bersyukur kepada Tuhan atas segala karunianya. Selain keyakinan agama yang kuat, hal yang juga mendukung ketenangan subyek ialah keberadaan mereka dalam lingkungan keluarga yang akrab satu sama lain. Diharapkan hasil penelitian ini -walaupun hasilnya belum dapat digeneralisasikan- dapat memberikan sumbangan pengetahuan dalam hal kematian yang masih sangat langka di Indonesia; kliususnya dari tinjauan ilmu psikologi, terutama bagaimana lansia mengatasi rasa takutnya terhadap kematian dan memberikan gambaran mengenai apa saja yang perlu dipersiapkan untuk dapat menghadapi kematian dengan tenang, sehingga mereka dapat mempergunakan sisa hidupnya dengan hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya.